 |
| Foto Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar, S.Sos. |
Detikacehnews.id | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek, mendesak Presiden Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memproses secara hukum oknum aparat yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil saat penyaluran bantuan kemanusiaan di Aceh.
Ceulangiek menilai, tindakan kekerasan yang terjadi di tengah situasi darurat bencana merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum, kemanusiaan, maupun etika kenegaraan. Menurutnya, masyarakat yang sedang tertimpa musibah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari negara, bukan perlakuan represif yang justru menambah trauma dan penderitaan.
“Tindakan kekerasan oleh aparat di tengah situasi bencana adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan melukai kepercayaan publik terhadap negara. Aparat seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menciptakan ketakutan di kondisi darurat,” tegas Ceulangiek.
Ia mengingatkan bahwa jika peristiwa tersebut tidak ditangani secara serius dan transparan, maka akan menjadi catatan kelam dalam sejarah Aceh serta berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat negara. Menurutnya, Aceh memiliki pengalaman panjang dengan konflik bersenjata, sehingga pendekatan keamanan yang tidak sensitif dapat membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya pulih.
Ceulangiek menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kekhususan tersebut lahir dari sejarah panjang konflik dan proses perdamaian yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan aparat negara di Aceh harus mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan psikologis masyarakat setempat.
“Pendekatan represif hanya akan memperlebar jarak antara negara dan rakyat. Padahal, kepercayaan yang telah dibangun selama masa perdamaian harus terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi bencana, negara seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh warga. Pendekatan humanis, persuasif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah aparat di lapangan.
Lebih lanjut, Ceulangiek mengingatkan bahwa keberadaan aparat TNI dan Polri di Aceh harus tetap mengacu pada ketentuan khusus yang telah disepakati dalam UUPA dan MoU Helsinki 2005. Dalam kesepakatan tersebut, jumlah personel TNI di Aceh dibatasi maksimal 14.700 personel dan Polri sebanyak 9.100 personel.
Menurutnya, pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan negara, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas, kepercayaan publik, serta memastikan pendekatan keamanan yang humanis dan sesuai dengan semangat perdamaian Aceh.
“Aceh memiliki kekhususan yang harus dihormati. Pembatasan personel dan pendekatan keamanan yang proporsional adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Aceh sebagai daerah yang memiliki akses langsung ke jalur internasional melalui laut dan udara. Dengan kondisi tersebut, stabilitas sosial dan keamanan harus dijaga secara bijak dan terukur. Pendekatan keamanan yang berlebihan, menurutnya, justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai semangat perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah.
“Aceh harus diperlakukan sesuai dengan kekhususannya. Pendekatan keamanan yang tidak humanis hanya akan memperburuk keadaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap negara,” pungkas Ceulangiek.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas dan objektif dalam menangani persoalan ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga dan stabilitas Aceh tidak terganggu, khususnya di tengah upaya pemulihan pascabencana.
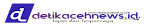
.jpg)
.jpg)


