 |
Oleh: Mahyani Muhammad [MM]. // Editor: Elga Safitri. |
Mahyani mengawali tulisannya dengan menyitir pandangan seorang sosiolog, Prof. Subanindyo Hadiluwih, Pd.D sekaligus sahabatnya terkait pasal fungsi sosial tanah dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia menilai bahwa realisasi fungsi sosial tanah pada praktiknya sering bias dan dimanfaatkan oleh oknum aparatur negara untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, narasi “fungsi sosial” kerap digunakan sebagai legitimasi untuk memuluskan praktik pengalihan hak tanah yang merugikan pemilik sah. “Pemilik tanah selalu dirugikan dengan ganti rugi di bawah nilai pasar, sementara mafia dan aparatur pendukungnya justru menikmati keuntungan,” ujarnya.
Mahyani juga menyoroti fenomena sosial yang menurutnya menggambarkan bagaimana niat sering dilacurkan demi pembenaran perilaku. Ia mencontohkan individu yang kerap menggunakan alasan “silaturrahmi” untuk bersantai di ruang publik, menikmati konsumsi gratis, dan mengabaikan tanggung jawab keluarga maupun produktivitas diri.
“Niat kerap digandakan. Narasi yang tampak baik di lisan tidak sejalan dengan tindakan. Itu bukan lagi kebenaran, tapi sekadar pembenaran,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa niat, dalam perspektif syariat, adalah tekad tulus yang menjadi dasar keabsahan perbuatan. Ketika tindakan tidak sesuai dengan pernyataan, publik dapat menilai bahwa niat tersebut telah dilacurkan.
Dalam bagian lain, Mahyani mengutip pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa bangsa hukum tidak menyelesaikan persoalan dengan teriakan, tetapi dengan pembuktian terang dan adil. Ia menilai saat ini banyak kritik di media publik yang kehilangan kaidah analisis, tidak berbasis fakta, dan sekadar alat tekanan politik.
“Banyak kritik hanya hadir sebagai pencarian panggung atau alat majikan politik,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa kritik yang tidak memenuhi kompetensi analitis dan landasan hukum justru menampilkan bias akhlak dan kapasitas pengkritik.
Mahyani turut menyinggung pandangan Prof. Ahmad Syafii Maarif yang menilai bahwa kritik di masa kini sering menabrak batas kehormatan dan rasa malu, sehingga kehilangan nilai dan makna.
Melanjutkan analisisnya, Mahyani menyebut sebagian pengkritik hanya tampil sebagai “pialang” dan bahkan “dayang” kepentingan tertentu. Ia menyebut mereka berada dalam koloni yang kehilangan panggung politik dan mencari kompensasi melalui riuhnya kritik.
Menurutnya, sebagian tokoh politik yang gagal mempertahankan posisi memilih tampil sebagai “mafia perpolitikan” demi mempertahankan akses ekonomi dan pengaruh.
Mahyani mengingatkan bahwa derasnya kritik bisa mengganggu pembangunan karena menurunkan semangat pemangku jabatan. Ia mendorong pejabat publik tetap melangkah elegan, tidak reaktif, dan fokus pada karya nyata sebagai jawaban terbaik atas kritik tidak berkualitas.
“Diam bukan menyerah. Diam yang bermakna adalah ketika seseorang terus bersinar melalui kinerja dan portofolio, bukan melalui perdebatan kosong,” tulisnya.
Ia menekankan bahwa publik lebih menghargai bukti kerja daripada pernyataan balasan. Pemangku kepentingan diminta menjaga ketenangan, mengedepankan kecerdasan emosional, sosial, intelektual, dan spiritual, serta terus bertumbuh tanpa membutuhkan validasi dari pihak yang meremehkan.
Mahyani Muhammad menegaskan bahwa kritik yang baik harus melalui kajian fakta, pertimbangan moral, dan keadaban. Sebaliknya, kritik yang berangkat dari niat buruk, kepentingan politik, atau bias personal hanya akan menjadi riuh tanpa makna di tengah dinamika masyarakat yang semakin terbuka.
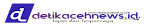
.jpg)
.jpg)


